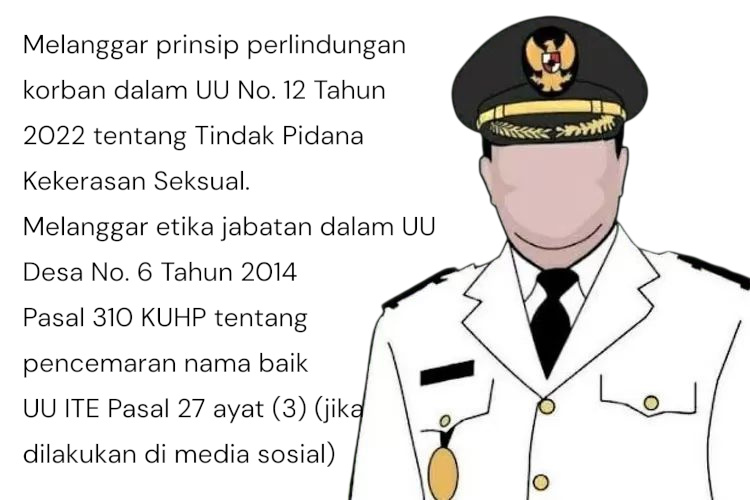TOTABUAN.CO BOLMONG — Ibrahim Nata, Kepala Desa Labuang Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), tengah menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diunggah melalui akun Facebook miliknya memperlihatkan pernyataan terbuka yang diduga memuat unsur fitnah dan pencemaran nama baik terhadap warganya sendiri, NL.
Dalam video tersebut, Ibrahim secara terang-terangan menyudutkan NL yang diketahui sebagai korban dari dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota Bhayangkari dengan menyebutnya sebagai “perempuan yang tidak baik”.
Pernyataan ini tidak hanya keliru, tidak berdasar, dan tidak etis, tetapi juga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum serta prinsip dasar perlindungan korban dalam sistem peradilan Indonesia.
Dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), negara menjamin perlindungan yang menyeluruh terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah non-stigmatisasi dan non-diskriminasi terhadap korban.
Apa yang dilakukan Ibrahim Nata justru sebaliknya. Alih-alih memberikan dukungan moral dan jaminan rasa aman kepada korban, ia malah menambah beban psikologis dengan narasi yang merendahkan, memojokkan, dan menyudutkan korban secara personal di hadapan publik. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik dan kekerasan verbal, yang tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga berpotensi mendorong masyarakat untuk turut menyalahkan korban atas kekerasan yang menimpanya sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah victim blaming.
Sebagai seorang kepala desa, Ibrahim Nata seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi warga desa, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan atau ketidakadilan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kepala desa adalah pelayan masyarakat, bukan alat kekuasaan yang bebas menghakimi warganya tanpa dasar hukum.
Pernyataan Ibrahim di media sosial menunjukkan sikap arogansi kekuasaan yang sangat berbahaya. Ia tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi melakukannya dengan kapasitas dan posisi strukturalnya sebagai pemimpin desa, yang tentu saja mempengaruhi opini publik. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan, dan mencerminkan buruknya pemahaman aparatur desa terhadap etika pemerintahan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
Tindakan Ibrahim patut diduga telah melanggar ketentuan hukum pidana, antara lain, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
Dalam pasal ini, seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan sesuatu yang tidak benar, dapat dikenakan pidana.
“Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena penyebaran pernyataan tersebut dilakukan melalui media sosial (Facebook), maka aturan ini juga berlaku, dengan ancaman pidana yang cukup berat,” kata salah pengamat Hukum Unsrat Manado.
Jika NL akan mengajukan laporan hukum,
maka Ibrahim berpotensi dikenai sanksi pidana ganda, baik dari KUHP maupun UU ITE.
Kasus ini merupakan contoh nyata dari rusaknya budaya komunikasi publik di tingkat pemerintahan desa, di mana pejabat publik merasa bebas berbicara dan menghakimi tanpa rasa tanggung jawab, empati, dan kepekaan sosial. Ini adalah alarm keras bagi negara dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi ulang sejauh mana pejabat di level desa dibekali pelatihan, pembinaan moral, dan pengetahuan hukum dalam menjalankan fungsinya.
NL bukan hanya sedang berjuang atas kekerasan fisik yang dia alami, tetapi juga sedang berhadapan dengan sistem yang masih kerap menempatkan korban sebagai pihak yang disalahkan. Tindakan hukum yang akan dia ambil bukanlah semata-mata untuk membela diri, tetapi juga untuk membuka jalan bagi korban-korban lain yang mungkin mengalami hal serupa. Normalisasi terhadap kekerasan simbolik, baik melalui ucapan, sindiran, hingga pencemaran nama baik, harus dilawan. Tidak boleh ada ruang bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi korban.
Ibrahim Nata bukan hanya harus mempertanggungjawabkan ucapannya di ruang publik, tetapi juga di hadapan hukum. Ini bukan semata-mata tentang konflik antara seorang kepala desa dan warganya, tetapi tentang tanggung jawab moral, hukum, dan etika pejabat negara terhadap rakyatnya. (*)